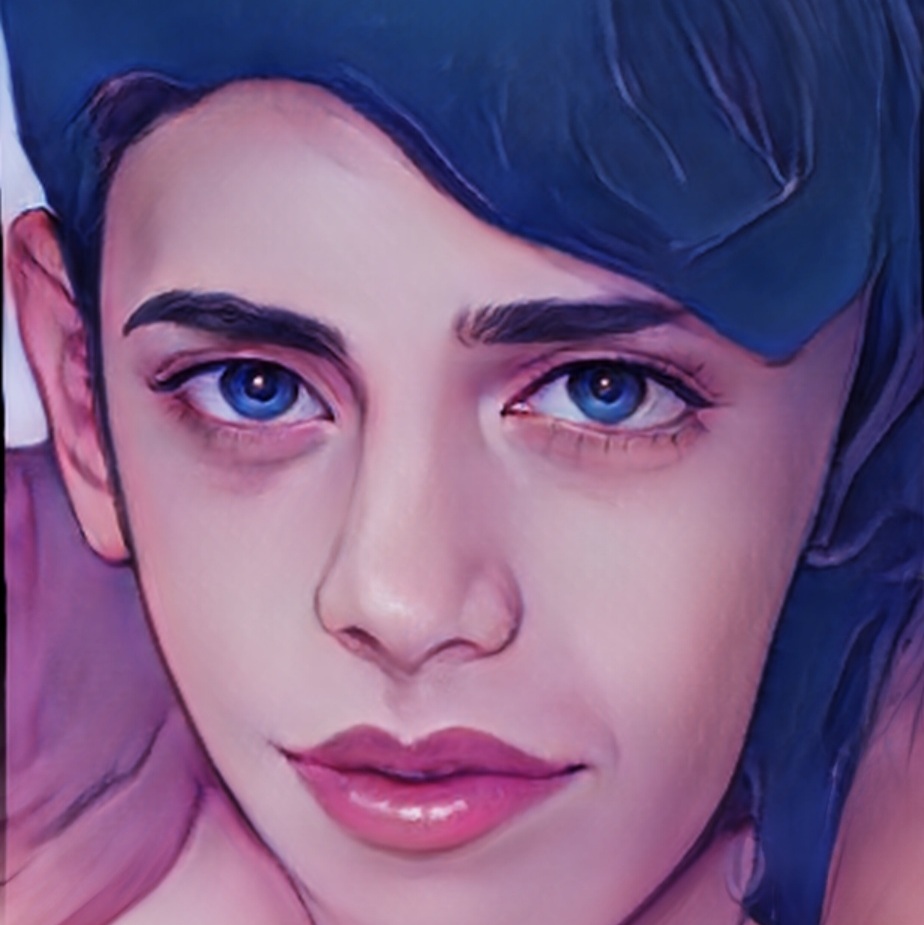Pagi masih belia ketika kami tiba di gerbang Surga. Sesuai dengan waktu terjungkalnya bus yang kami tumpangi. Kisahnya begini. Pagi itu, bus yang membawa kami dari desa Rimbun Raya ke kota Gersang Amat melaju dengan kecepatan tinggi. Di sebuah tikungan tajam, seekor sapi menyeberang jalan. Sopir terkejut. Dibantingnya stir ke kanan. Sapi sialan itu bisa dihindari. Tapi dasar sial, mobil terlanjur masuk got. Jadilah, di pagi buta itu beramai-ramai kami menghadap St. Petrus di gerbang Surga.
“Pagi-pagi kok sudah ramai, ada apa ni?”, tanya St. Petrus. Memang situasi sangat gaduh. Masing-masing ingin duluan menghadap St. Petrus. Ini kan biasa. Di dunia saja orang selalu ingin yang terdahulu. Mana ada yang rela antri berlama-lama. Kalaupun ada bisa dihitung dengan jari.
“Begini bapak Petrus, ya, kami ini kan sudah mati. Terus kami mau minta kejelasan tentang nasib kami. Kan tempatnya di sini, to?”, kata seorang ibu yang dari tadi paling banyak omongnya.
“Memangnya ada apa, ni. Kok matinya rame-rame?”, tanya St. Petrus lugu, atau pura-pura bloon?
“Masa bapak Petrus tidak tahu? Apa di Surga sini belum ada koran pagi?”, kata jubir kami yang caleg partai ‘Pilihlah Saya’ itu.
“Ada, sih, cuman saya belum sempat baca. Habis tamunya dua puluh empat jam non stop, sih”, kata St. Petrus cemberut.
“Omong-omong, nasib kami bagaimana, ni?”, tanya jubir kami.
“Begini, ya, sekarang jaman reformasi. Setiap orang bebas memilih, apa mau Surga atau Neraka. Setiap orang boleh melakukan observasi di Neraka maupun di Surga, masing-masing dua puluh empat jam. Kemudian baru menjatuhkan pilihan”, kata St. Petrus menjelaskan.
“Kok, pilih sendiri? Kan bapak Petrus seharusnya sudah tahu siapa yang layak masuk Surga atau Neraka”, protes jubir kami.
“Loh, bukankah reformasi ini berdasarkan desakan dari bawah? Pokoknya sekarang tidak ada lagi ‘instruksi’ dari atas. Katanya tiap orang harus bebas memilih? Sudah, sekarang waktunya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melakukan observasi”, kata St. Petrus.
Seorang pegawai Lusifer membawa kami ke Neraka. Begitu pintu gerbang Neraka dibuka, tampaklah sebuah tempat parkir yang luas. Ribuan mobil mewah diparkir di sana. Kami saling memandang. Heran. Keadaan Neraka sama sekali lain dari yang biasa digambarkan di dunia. Tidak ada api, tidak ada ratapan, tidak ada kertakan gigi. Di pintu gerbang kedua kami disambut oleh banyak orang yang berdandan rapih. Mereka adalah orang-orang yang kaami kenal. Perjamuan yang diadakan untuk kami digelar dalam sebuah ruangan maha luas. Banyak makanan dan minuman. Kamar tidur yang disiapkan untuk kami seukuran dengan hotel yang paling banyak bintangnya di Indonesia. Ketika bangun, pegawai Lusifer sudah siap menghantar kami kembali ke gerbang Surga. Waktu observasi di Neraka selesai. hasilnya sangat memuaskan.
Survei ke Surga dimulai. Seorang Malaikat menemani kami sebagai pemandu. Kami dibawa ke suatu tempat yang luasnya melebihi Neraka. Sangat banyak orang di sana. Semua dalam dandanan putih. Bersama para Malaikat, mereka terus menyanyi: Kudus… kudus… kudus…”. Begitu mempesona, hingga waktu dua puluh empat jam berlalu tanpa terasa. Malaikat pemandu kami mengajak kami pulang. Hasil observasi sangat memuaskan.
”Bagaimana, mau pilih yang mana?”, tanya St. Petrus, ketika kami kembali ke hadapannya. “Dua-duanya sama-sama menarik”, kata jubir kami, yang dalam observasi tadi paling banyak bertanya. “Tapi harus pilih salah satu”, St. Petrus menyambung. “Ini butuh refleksi, bapak Petrus. Kami butuh waktu”, kata sang jubir genit. Bikin gemas. “Tapi jangan lama-lama”. Kamipun tenggelam dalam refleksi masing-masing.
Dan ketika kami sedang bermenung, St. Petrus mendengungkan lagu ini: “Janji… janji… tinggal janji…”, membuat kami penasaran. Sehingga ketika waktu refleksi usai, jubir kami langsung bertanya, “Bapak Petrus tahu lagu yang pernah tenar di Indonesia itu? Padahal orang Indonesia sendiri sudah tidak ingat lagi”.
“Memangnya aneh?”, sergah St. Petrus. “Bukan apa-apa, sih. Cuma tanya”, jawab sang jubir semakin genit.
“Omong-omong, setiap orang harus menjatuhkan pilihannya sekarang”, kata St. Petrus. Sang Jubir yang pertama memilih.
“Bapak Petrus yang saya hormati, setelah mengamati, menimbang dan memperhatikan dengan seksama, maka saya memutuskan dengan sesadar-sadarnya untuk memilih Neraka. Karena ternyata Neraka tidak seburuk yang digambarkan oleh orang-orang dunia”, katanya.
Dan, entah mengapa, semua menjatuhkan pilihan pada Neraka. Pegawai Lusifer bertepuk tangan, dan mengajak kami pergi. Kami semua melambaikan tangan kepada St. Petrus, yang terus bernyanyi, malah semakin keras dan senduh, “Janji… janji… tinggal janji…”. Kami menggeleng-geleng keheranan. Pasti ada yang kurang beres.
Ketika gerbang Neraka dibuka, terkejutlah kami semua. Tempat parkir yang luas itu tidak ada lagi. Sebagai gantinya, tampaklah lautan api yang mahaluas. Sejauh mata memandang hanyalah api. Orang-orang yang menyambut kami saat observasi sedang merintih pilu, menahan kesakitan. Mereka menangis, tapi tiada lagi air mata yang keluar. Jubir kami mengajukan protes,
“Tidak ini bukan tempat kemarin. Kita salah masuk”. “Tidak. Kita benar. Ini tempatnya”, kata pegawai Lusifer yang menghantar kami. “Kalau begitu, ini penipuan”, kata sang jubir lagi.
“Loh, ini kan biasa. Di dunia juga ada ‘trik’ ini, bukan? Untuk menarik minat pembeli, orang membuat iklan yang menarik. Untuk mendapatkan sesuatu, orang harus menunjukkan yang terbaik. Untuk mendapat dukungan rakyat saat pemilu, orang membuat janji-janji yang muluk-muluk. Biasa, bukan?”, kata sang pegawai membela diri. “Tidak, ini penipuan. Kapan dan dimanapun juga, entah di Surga ataupun di bumi, penipuan tetaplah penipuan. Harus diproses secara hukum”, teriak kami serempak. Tapi tak ada yang mendengarkan protes kami.
Sementara hawa panas semakin mendekat dan perlahan-lahan kulit kami menghitam. Akhirnya dengan kemampuan yang sisa, kami ulangi lagu yang dinyanyikan St. Petrus tadi, “Janji… janji… tinggal janji…”, sampai tenggorokan kami benar-benar kering. Dan pada saat itu aku berteriak sambil membanting diri. Sialan, aku terpelanting dari tempat tidur. Mimpiku yang buruk itu berakhir, tapi wajahku yang terbentur pada lantai masih menyisakan rasa sakit. ***(Kpg 27 Maret 2004)
Catatan Redaksi: Cerpen Karya GS John – Cerpenis NTT asal Malaka. Karya ini pernah publikasi di Harian Umum Pos Kupang dan diabadikan dalam Buku kumpulan Cerpen: “Tapak-Tapak Tak Bermakna”, terbitan Penerbit Ledalero, Maumere, Flores 2005.